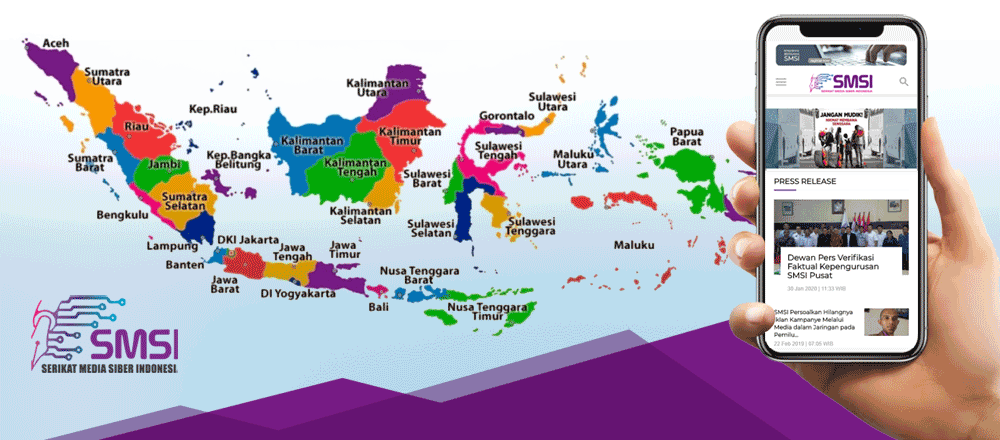INFOTANGERANG.CO.ID – Dalam ruang terapi, orang membayar untuk disembuhkan. Di ruang redaksi, jurnalis dibayar untuk bertahan menghadapi realitas. Keduanya mencari cara berdamai dengan kenyataan yang tak selalu ramah, tetapi dengan dinamika yang berbeda.
Jurnalisme bukan sekadar pekerjaan teknis menulis dan melaporkan. Ia adalah profesi yang menuntut kehadiran batin penuh: menyimak, menimbang, dan memutuskan apa yang layak dipercaya publik. Seorang jurnalis harus cukup dekat untuk memahami, namun cukup jauh untuk tidak larut. Ketegangan ini bukan drama personal, melainkan prasyarat kerja.
Fakta jarang datang dalam kondisi steril. Ia dibungkus emosi narasumber, kepentingan beragam pihak, dan desakan waktu. Bekerja di tengah kepadatan ini memerlukan kewaspadaan konsisten. Kelelahan yang menyertai bukan sekadar keluhan personal, melainkan konsekuensi struktural dari tuntutan perhatian mendalam yang berkelanjutan.
Setiap liputan memerlukan penilaian berlapis: relevansi, keseimbangan, dan dampak publikasi. Proses menimbang ini menguras fokus dan energi kognitif. Dalam arti tertentu, jurnalisme menyerupai terapi sebuah latihan rutin menghadapi kenyataan tanpa menutup mata.
Belajar Tanpa Henti di Medan yang Berubah
Dalam perspektif sosiologi profesi, jurnalisme adalah bentuk continuous professional learning proses belajar yang tak pernah selesai karena medan kerjanya terus berubah. Seperti dikemukakan Donald Schon tentang reflective practitioner, profesi yang berhadapan dengan ketidakpastian menuntut refleksi terus-menerus dalam tindakan.
Informasi datang tak utuh, waktu terbatas, tekanan mengiringi. Keputusan editorial lahir dari penilaian reflektif yang diasah pengalaman, bukan rumus baku. Setiap liputan adalah kelas baru; setiap naskah adalah ujian yang kerap datang mendadak.
Koreksi redaktur bukan sekadar penyuntingan teknis, melainkan evaluasi cara berpikir, ketepatan sudut pandang, dan ketahanan argumen. Proses ini membentuk habitus profesional yang tertanam melalui praktik harian.
Tuntutan Kerja Emosional yang Tak Terlihat
Banyak profesi modern, termasuk jurnalisme, menuntut emotional labor kemampuan mengelola perasaan agar selaras dengan tuntutan peran. Jurnalis diharapkan empatik tanpa larut, kritis tanpa sinis, objektif tanpa beku. Keseimbangan ini dipelajari secara implisit melalui koreksi, teguran, dan pengalaman lapangan.
Di era digital, tekanan kecepatan mempertebal kompleksitas. Ruang refleksi menyempit sementara tuntutan akurasi tetap tinggi. Kerja belajar jurnalis menjadi berlapis: belajar fakta, belajar konteks, sekaligus belajar mengatur ritme berpikirnya sendiri.
Terapi yang Membutuhkan Dukungan Ekosistem
Menyebut jurnalisme sebagai terapi bukan berarti menganggapnya obat mujarab. Terapi bekerja dengan batas, durasi, dan kesadaran risiko. Penting menghindari romantisasi bahwa kelelahan adalah tanda pengabdian atau luka batin adalah prasyarat profesionalisme.